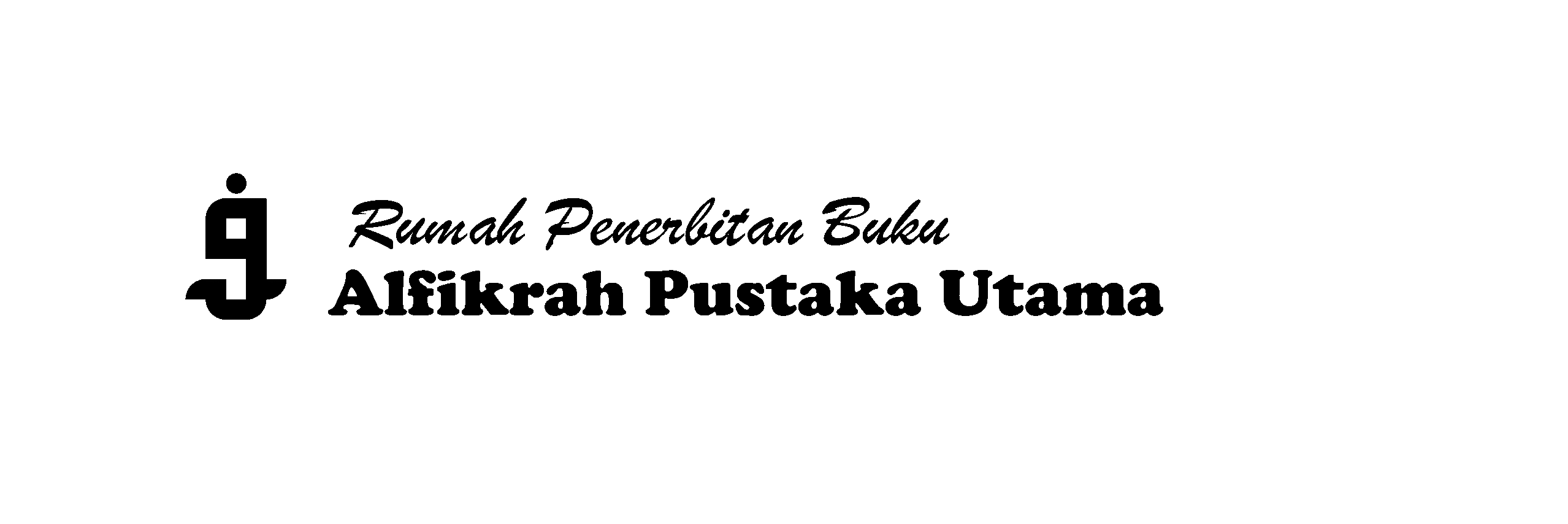Dulu, istilah-istilah hermeneutika tak begitu banyak yang saya dengar. Bahkan bisa dikatakan tak ada dorongan untuk mencari tahu persoalan dunia linguistik yang demikian. Namun nyatanya dorongan itu tak diperlukan lagi, cepat atau lambat dunia tulis-menulis akan mengantarkan siapapun yang menjamahnya pada ruang filsafat-filsafat teks itu.
Apakah saya seorang penulis? lalu apakah saya bisa menulis? apa bukti saya bisa menulis? kaidah apa yang saya gunakan untuk menulis?. Kiranya sekumpulan pertanyaan itu yang berulangkali membuat saya tersendat. Ide di kepala dan teknik ala kadarnya sering bertarung hebat, bagai juru masak yang membubuhkan bumbu seadanya dan sepahamnya. Saya merasa hambar atau tidaknya tulisan yang keluar dari meja ketik saya, adalah kapasitas seadanya yang saya sendiri tidak tahu barometernya. Hemat saya, menulis bagi saya adalah mengulir gagang kran air yang mati. Tumpah, deras, dan segar.
Soal perjumpaan pertama pada hermeneutik, saya pernah mengunyah bahasa tulisan Gus Al-Fayyadl pada bukunya — Derridean. Sepanjang 2018 tepatnya, buku-buku semacam itu menggeluti hari-hari di kelas perkuliahan. Naasnya saya tak paham begitu dalam. Namun setidaknya buku itu sedikit memantik kesimpulan praktis yang saya ambil bahwa, dekonstruksi teks merupakan bentuk final akan pernyataan bahwa penafsiran akan teks tidak akan benar-benar final.
Selepas dari jeratan kepentingan keilmiahan di dunia perguruan tinggi, saya mencoba kembali banting setir. Sepulangnya dari Jogja, saya coba kumpulkan catatan harian selama empat tahun di sana. Alhasil, catatan itu hanya menjadi bahan refleksi dan tak ada yang menjadi sebuah laporan penelitian ngilmiah selayaknya akademisi. Sepertinya niatan banting setir itu kian menguat, segera berbelok tajam, menukik sampai pada kesenjangan gaya bahasa. Ya, sampai saat ini menulis ala kadarnya, sastra abal, hingga sekadar menumpah jenuh telah mengisi hari-hari penghidupan saya daripada gaya tulisan yang selainnya.
Lalu apakah teks yang saya tulis mati? redup? nirkonsep? nirlogika?, dalam hal ini persoalan standarisasi keilmiahan yang diagungkan di kelas-kelas perguruan tinggi. Saya akui memang benar adanya. Saya bukan peneliti, bukan pakar, atau bahkan bukan akademisi yang kritis pada segala realitas persoalan dunia ini. Saya hanya pembaca buku dan penulis yang terjun bebas menumpahkan hasrat isi kepala.
Suatu waktu pembelaan itu datang. Semacam pemberi secercah harapan akan inferioritas yang membuat saya berkabung berkali-kali soal tulisan sendiri. Gadamer terbela habis-habisan oleh Mas Fathul Panatapraja dalam karyanya Al-Muallaqat. Saya pun membaca sambil mengernyitkan dahi,
“Bukankah, dalam kenyataan, setiap kesalahpahaman mengandaikan sebuah ‘kesepemahaman umum yang mendalam’? Kita berkata misalnya, bahwa pemahaman dan kesalahpahaman terjadi di antara aku dan engkau. Namun rumusan ‘aku dan engkau’ sudah menghianati keterasingan yang luar biasa, Tidak ada sesuatu pun seperti ‘aku dan engkau’ sama sekali — tidak ada entah aku atau engkau sebagai sesuatu yang terisolasi kenyataan-kenyataan substansial. Aku boleh mengatakan ‘engkau’ dan aku boleh mengacu pada diriku sendiri terhadap suatu engkau, tetapi sebuah kesepahaman (Einverstandis) selalu mendahului situasi-situasi ini. Kita semua tahu bahwa mengatakan ‘eng’au’ kepada seseorang mengandaikan sebuah kesepahaman mendalam (tiefes Einverstandis). Sesuatu yang bertahan telah hadir ketika kata ini diucapkan.”
Sulit mengerti?, sama. Sore itu Cihapit Bandung diguyur hujan deras. Dua cuanki pikul sudah meneduh dengan radius yang sama-sama masih terlihat oleh mata ini. Al-Muallaqat dan syair-syair pilihan penulisnya masih saya teguk pelan-pelan.
Hans Gadamer adalah tokoh penting yang menjembatani ketegangan penafsiran teks di zaman filsafat memasuki era pasca modern — pasca kemapanan. Pada intinya, setiap teks itu dinyatakan bebas tafsir oleh pembacanya. Bahkan lebih radikal lagi, Derrida mengatakan bahwa setiap penulis telah mati kala tulisan itu sudah selesai ditulis pengarangnya.
Membaca narasi yang tandas itu saya kemudian gamang, lantas kala teks ilmiah harus mengantongi nilai rasionalis positivistik ala Cartesian, bagaimana bisa ia runtuh dengan nalar yang jelas-jelas bertolak belakang?. Begini, maksud saya bukankah tak etis jika harus mengatakan setiap penelitian ilmiah itu pasti harus salah?, bahkan sebelum teori baru itu dilahirkan?. Atau begini saja, secara logika bebas kita bisa mengatakan sebelum kebenaran itu lahir melalui teks, ketakbenaran sudah mendahaluinya melalui pembaca yang akan ditemuinya.
Kira-kira begitulah nama-nama seperti Heidegger, Dilthey, Schleirmacher, hingga murid-muridnya berseteru. Schleirmacher si ahli hermeneutis romantis yang selalu melibatkan prasangka psikis penulis, Dilthey si pakar hermeneutik praktis yang terpengaruh lingkungan industustrialis, hingga Heidegger yang pikirannya masih di langit tertatih berusaha menggapai teks yang nun jauh di bumi. Gadamer sejatinya sama, namun lebih tak ingin bersitegang berkepanjangan.
Sampai sini saya akan memperjelas bahwa, “sebuah teks” oleh siapapun yang menulis adalah sekumpulan tafsiran yang mengalir. Ilmiah atau tidak, bahasa baku atau gurauan populer, berdasarkan data atau hanya ingatan kolektif, adalah serangkaian yang sama. Si penulis dan pembaca saling mengembangkan resonansi untuk mencapai satu titik temu yang lebih mendekati sebuah kebenaran.
“Allez Schriftliche ist in der Tat in bevorzugter Weise Gegenstand der Hermeneutik” (semua yang tertulis di kenyataan lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika).
Saya tetap sebagai sudut pandang penulis yang tengah sibuk memproduksi tulisan-tulisan yang tak berujung muaranya. Setidaknya kian yakin dan percaya diri bahwa sebuah tulisan lahir seharusnya tak lagi menyoal tendensi model, bentuk, kerangka, motif, skills, atau bahkan kelas sosial penulis. Melalui pernyataan Gadamer di paragraf atas (“Bukankah, dalam kenyataan…) setidaknya ada satu pembelaan kuat bahwa memahami teks baik si penulis maupun pembaca adalah melibatkan pengalaman keduanya (dialektis bukan sekadar metodologis). Kita adalah dua kutub yang silih berganti itu, esok boleh jadi menulis, esok pula boleh jadi membaca.
Begitulah yang kiranya digaungkan Gadamer. Pembaca dan penulis pasti berjarak. Selera, pengetahuan, kebutuhan, dan segala hal yang mendasari keduanya ada, pasti melahirkan satu horizon kebenaran. Ketaksepahaman selayaknya seni yang berjalan. Mungkin terlalu jauh jika harus mengatakan jika teks harus berdampak pada khalayak luas, tapi setidaknya setiap penulis dan pembaca adalah dua kutub yang melahirkan seni penafsiran kebenaran yang terus berkelanjutan itu.
Jangan takut menulis, jangan berhenti pula membaca. Tabik
Muhammad Farhan, cerpenis dan kolumnis. Lulusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,