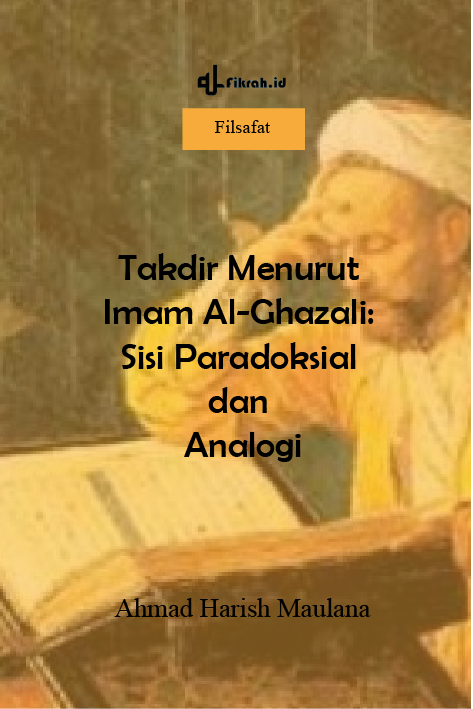Kebangkitan berpikir di abad pencerahan Eropa agaknya semacam pengulangan apa yang dilakukan peradaban sebelumnya. Yunani, atau Islam boleh jadi. Namun begitulah hebatnya bangsa barat dalam kegiatan perebutan hak paten pemikiran. Secara logika bebas, istilah rasio dan empiris setidaknya mengulang apa itu dunia ide Plato dan apa itu hukum aktualitas-potensial Aristoteles. Semua berputar masalah pencarian kebermulaan sesuatu ; dalam hal ini adalah kebenaran.
Kalau dalam peradaban Islam mungkin tak dirunyamkan soal yang demikian. Hanya saja edisi peradaban Islam dihadapkan pada kedatangan teks wahyu yang posisinya diperdebatkan antara sumber kebenaran ataukah sumber verifikasi kebenaran. Mudah kata Islam dihadapkan pada superioritas akal (tak berwujud) dan superioritas teks wahyu (yang berwujud).
Mari kita sederhanakan dengan perumpamaan yang mudah. Bagi Plato, realitas dan ide itu berbeda. Dunia ide itu sebagai realitas sejati dan murni yang menjadi asal muasal pengetahuan sejati (Pembaca bisa melihat analogi goa Plato yang sudah cukup masyhur). Mudah kata, Plato menghendaki muara kebenaran bersifat satu dan universal.
Namun Aristoteles membantah bahwa tujuan memuarakan kebenaran menjadi satu telah mengesampingkan banyak hal. Aristoteles memilih sebuah istilah entelechia (aktualitas) dan dunamis (potensialitas) sebagai bentuk kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Aristoteles menganggap segala kesimpulan dari pencarian sebuah kebenaran adalah kebenaran, sampai menuju muara kebenaran. Dari gagasan ini kita semacam tak bisa menyalahkan bahwa biji mangga itu bukan mangga. Tapi ia adalah benar-benar mangga namun masih berwujud biji.
Selesai di akhir perdebatan demikian, muncul tantangan yang sama dalam bentuk zaman teks pewahyuan. Peradaban Islam melanjutkan dengan dua hal ; pertama, melanjutkan tradisi perdebatan dua kubu ala Yunani kuno itu. Kedua, memiliki fokus tradisi sendiri yaitu seputar peletakan wahyu dalam pembuktian Tuhan.
Teks wahyu datang dengan mapan. Instrumen suci yang tak mungkin lagi memiliki kecacatan pemberitaan. Namun faktanya, mazhab pemikiran juga bermunculan begitu deras dengan segenap argumen kuat para penuturnya. Aliran dalam Islam muncul begitu sporadis, baik kalam, fikih, dan bahkan tasawuf sekali pun.
Singkat pembahasan, kemunculan itu setidaknya juga bermutar masalah “kebenaran” itu jelas dari yang berwujud (teks wahyu), atau “kebenaran” itu adalah proses berpikir dalam dunia ide (akal) yang mungkin tak bisa digambarkan bentuk intelejensianya. Pada akhirnya tawaran baru pun muncul dengan mengambil jalan tengah dengan munculnya aliran-aliran yang menghindari fanatisme ke arah kiri maupun kanan, bahkan mungkin hingga kini. Corak inilah yang menjadi kekhasan pemikiran teologis untuk menjembatani ketegangan kedua belah pihak.
Descartes dan Hobbes
Kita beranjak lebih jauh, Eropa bangkit dengan wajah baru. Peristiwa yang dilabeli Rennaisance (kebangkitan seni dan kebebasan ekspresi) dan Aufklarung (kemunculan tradisi berpikir) itu sebetulnya pengulangan yang sama. Perancis melahirkan nama besar seperti Rene Descartes dengan berjilid-jilid karya meditasinya. Julukan besar disematkan padanya sebagai bapak filsafat rasionalis yang menelurkan banyak aliran di bawahnya. Singkat penjabaran, buku Meditation on First Philosophy ingin menggaungkan bahwa, “akal punya cara sendiri untuk menemukan kebenaran, tanpa tendensi piranti lainnya.” Terdengar prestisius. Alih-alih itu menjadi temuan baru dan termutakhir, justru masih dalam satu periode hidup Descartes, buku besar “Leviathan” Thomas Hobbes lahir mengkritik habis karyanya.
Hobbes mmenawarkan istilah sense atau indera sebagai piranti kebenaran, yang kemudian pemikiran ini melahirkan aliran empiris (pengalaman).
The original of them all is that which we call sense, (for there is no conception in a man’s mind which hath not at first, totally or by parts, been begotten upon the organs of sense).
Asal mula semuanya adalah apa yang kita sebut indra, (karena tidak ada konsepsi dalam pikiran manusia yang pada awalnya, secara keseluruhan atau sebagian, tidak dilahirkan dari organ indra).
Begitu kata Hobbes di awal tulisannya. Tentu hal ini menjadi satu perdebatan paling panas di Eropa sedari abad enam belas. Sampai-sampai dua kubu ini melahirkan banyak variasi mazhab yang terus saling singkur.
Warisan Pemikiran
Baik Descartes maupun Hobbes dengan segenap pemikir setelahnya setidaknya telah memberikan warisan besar. Nyatanya rasio akal dan pengalaman adalah satu kesatuan yang mungkin sukar untuk dipisah. Bagi Descartes rasio akal mampu melahirkan logika matematis untuk merumuskan kebenaran. Akan tetapi pengetahuan akan kebenaran itu juga merupakan sebuah proses yang panjang dari adanya pengalaman inderawi.
Membenturkan keduanya terkadang menimbulkan semacam tasalsul, keberputaran yang tak berujung. Sehingga bisa dipastikan ketika penganut masing-masing mazhab ini bertemu dan tak memiliki konklusi universal, maka kecacatan logika terhenti akibat sisi pragmatis masing-masing.
Permisalan mazhab rasionalis sederhananya begini,
sebuah hukum universal mengatakan :
- semua makhluk akan mati,
- manusia adalah makhluk,
AB. manusia akan mati (Rasio).
Sedangkan banyak kasus yang mempertanyakan logika matematis ala Descartes itu. Bagi Hobbes pengetahuan tetap harus melalui pintu indera. Hemat kata, rumusan logika itu tak akan muncul ketika Desacartes tak mengetahui bentuk kebenaran akan “kematian” tanpa adanya proses melihat dan mendengar. Entah berbentuk pengalaman primer (yang dirasakan langsung) maupun sekuder (dari pemberitaan orang lain). Maka seorang yang belum genap intelejensianya, seperti layaknya seorang balita, tak akan mampu menjawab sedemikian rumusan logika itu.
Serasa kian bernas terdengar. Tapi tentu ketika model Hobbes itu dikrititisi ulang masih menyimpan sebuah celah. Penginderaan tetap membutuhkan nalar verivikatif. Indera tetap terbatas, dan logika matematis tetap dibutuhkan. Permisalan seorang balita tak bisa dijadikan sebuah kebenaran final. Boleh jadi saat seorang balita disandingkan dengan seseorang yang tak mampu melihat akan berbeda reaksi melihat sebuah realitas kematian. Seorang balita walau tak mampu menarasikan sebuah kematian dengan bahasa, ia tetap bisa memberikan reaksi pada banyak realitasnya ; makam, peti, hingga raut tangisan banyak orang. Maka bisa disimpulkan logika rumusan logika di awal adalah benar secara universal tanpa harus mempertimbangkan sebab-sebab lain.
Bantahan selanjutnya sudah dipastikan menemui titik celahnya kembali. Para penganut empiris tetap akan membantah bahwa pernyataan keduanya (balita dan seorang tunanetra) tetap sama-sama memiliki kebenaran. Kematian bagi keduanya sama, namun narasi yang dijabarkan berbeda. Bisa jadi seseorang tak melihat realitas kematian, tapi bisa merasakan kehadiran realitas itu sendiri. Mati itu sakit, mati itu dikelilingi tangisan, mati serupa cerita-cerita penyiksaan, dan banyak hal selainnya. Terdengar kian meluas dan tetap tak berujung.
Pengulangan Yang Sama
Sampai sini mungkin kita bisa melihat bahwa apa yang dibawa Desacrtes dan Hobbes juga merupakan perjalanan perdebatan pemikiran seperti peradaban sebelumnya. Keduanya masih tak lepas dari persoalan materi (indera) dan immateri (rasio). Sepanjang khazanah pemikiran baik peradaban Yunani, Islam, hingga Eropa abad pertengahan hingga modern masih berkutat pada dua hal tersebut. Atau bahkan hingga kini kiranya. Hanya saja bentuk ataupun model perdebatannya yang berbeda. Namun pada akhirnya keduanya tak memiliki ruang untuk hidup sendiri. Keduanya beriringan, saling mengoreksi, mengkritik, dan membetulkan celah-celah yang kosong. Kadang kesempurnaan memang terlalu jauh untuk dicapai, sedangkan pencapaian sendiri itu sebetulnya sudah kesempurnaan.
Rujukan bisa dilihat langsung dalam dua karya besar ; “Meditation On First Philosophy” dan “Leviathan.”