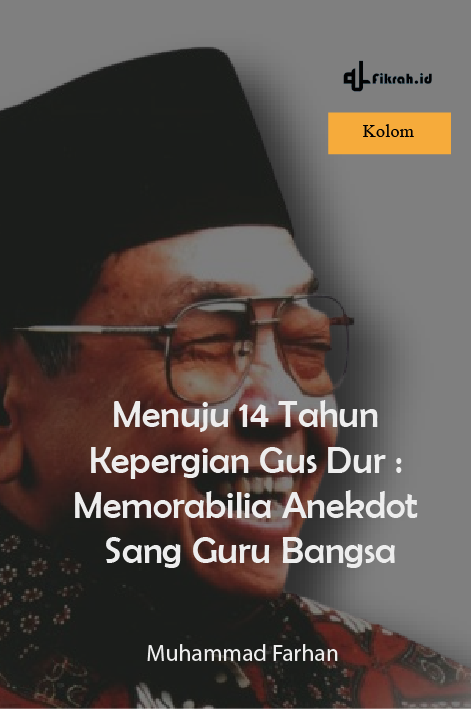Tak dapat dimungkiri jika dalam suatu kelompok, komunitas, besar ataupun kecil selalu membutuhkan sosok pemimpin. Seperti di dalam keluarga atau skala yang lebih besar negara, misalnya. Hal ini terjadi dikarenakan secara naluri manusia menghendaki kehidupannya untuk terarah pada tujuan yang sama, yaitu kebaikan. Demi mencapai hal tersebut secara efektif maka tumbuhlah ide kepemimpinan. Kendati melihat fungsinya yang demikian itu, sosok pemimpin yang muncul tidak selalu berhasil memberikan pencerahan sebagaimana seharusnya, tapi justru sebaliknya, yaitu memperburuk keadaan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka perlu sekiranya memahami fenomena kepemimpinan.
Kepemimpinan Sebagai Fenomena
Kenapa perlu mengevaluasi ulang soal kepemimpinan? Hal ini perlu sedikit penguraian mengingat isu tersebut cukup klinikal, dalam arti memberikan pengaruh, sedikit atau banyak, pada setiap aspek kehidupan manusia. Sekiranya ada dua poin penting dalam hal ini: Pertama, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang sekadar bersifat peristiwa (event), tapi juga merupakan sebuah fenomena (phenomenon). Apa maksudnya? Sebagai fenomena menggambarkan bahwa ia merupakan sesuatu yang sudah, sedang dan akan selalu eksis di dalam peradaban manusia. Jika demikian cara melihat isu kepemimpinan, maka seseorang tidak akan terjebak atau terlalu berfokus terhadap perkara yang bersifat insidental (misalnya, pemilu yang diadakan setiap lima tahunan). Kedua, dikarenakan kepemimpinan adalah sebuah fenomena, maka ia perlu dipahami dari sisi karakteristiknya. Maksudnya ada perwatakan yang lahir melalui kepemimpinan dalam bentuk figur individu. Dalam konteks diskursus kekinian secara sederhananya dapat kita bagi menjadi dua, watak otoriter dan demokratis.

Refleksi Melalui Figur Nabi Muhammad Saw.
Beragam watak telah dipertontonkan dalam mengemban amanat kepemimpinan. Sejarah telah memberikan beragam referensi untuk dirujuk. Jika mengikuti kategorisasi sebelumnya, antara watak otoriter dan demokratis, maka bisa diberikan permisalannya. Watak pertamabisa digambarkan melalui keberadaan manusia seperti Fir’aun yang kehadirannya membawa watak buruk dari kekuasaan, seperti sombong dengan menganggap dirinya sebaga tuhan dan berkata, “Akulah tuhan kamu yang paling tinggi” (lihat QS. an-Nazi‘at: 24), meremehkan martabat manusia dengan membunuh semua anak laki-laki (lihat QS. al-Baqarah: 49) hanya karena rasa takut akan hilangnya kekuasaan dan sewenang-wenang terhadap manusia lainnya (lihat QS. al-Qashas: 4).Seluruh perwatakan tersebut terekam dalam Alquran dan sejarah peradaban untuk dijadikan sebagai pembelajaran generasi yang hidup setelahnya.
Melihat perwatakan otoriter sedemikian rupa, patutlah muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya laku seorang pemimpin? Dalam hal ini sangatlah pantas dan patut jika kita melihat figur Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan sepanjang masa dan bagi seluruh umat manusia. Anggapan demikian tidaklah berlebihan, tersebab sudah dibuktikan secara faktual dan tercatat oleh sejarah. Figur Nabi Muhammad Saw. dalam soal kepemimpinan telah diperlihatkan dalam setiap aspek kehidupannya. Ia hadir sebagai pemimpin dalam posisinya sebagai nabi, penuntun manusia pada pencerahan hidup, juga sebagai kepala keluarga, kepala militer, bahkan kepala negara. Untuk hal terakhir ini sejarah telah mencatat keberhasilannya dalam memimpin ragam umat di Madinah berlandaskan nilai-nilai demokratis. Nabi Saw hadir, pada saat itu, sebagai sosok pemimpin, dengan strategi menanamkan perasaan aman kepada seluruh penduduk kota, juga mengelola perbedaan yang ada demi mencapai kebersatuan bermasyarakat yang hakiki. Dalam hubungannya dengan non muslim, terutama kelompok Yahudi, Nabi bermusyawarah dengan mereka untuk membentuk suatu kesepakatan. Sehingga dengannya masing-masing pihak dapat menikmati kebebasan dalam hal muamalah, ibadah dan berpendapat. Dengan demikian, rasa aman hadir dalam jiwa mereka dan terjaminlah persamaan hak dalam kedudukannya sebagai manusia seutuhnya. Kesepakatan ini dinamakan dengan istilah ‘Piagam Madinah’, terjadi pada tahun pertama Hijrah, sebelum perang Badr (Musdah Mulia, Negara Islam, 211-213).
Dalam konteks kepemimpinan, paling tidak ada 4 karakter yang melekat pada diri nabi sebagai ide penuntun, dikutip dari kitab Tuh{fatul Murid ‘Ala Jauharat al-Tauhid karya Imam al-Baijury: Amanah, yaitu menjaga secara zahir dan batin dari hal-hal yang tercela. Secara zahir mereka terlindung dari zina, meminum khamr, berbohong dan selainnya. Secara batin mereka terjaga dari kedengkian, kesombongan, riya dan selainnya. Dengan watak demikian, seseorang akan merasa aman jika mempercayakan sesuatu padanya. Shidq, karakter terkait dengan yang pertama, bahwa ucapan yang keluar dari lisannya sesuai dengan apa yang terjadi, kemudian sifat jujur tersebut juga menjadi kunci dalam posisinya sebagai nabi, yaitu dakwah risalah dan hukum-hukum syariat. Fathanah, kecerdasan yang terwujud dalam sikap waspada dan sigap dalam menghadapi lawan dan menyangkal motof-motif palsunya dengan kemampuan logika (hujjah) yang kuat. Tabligh, yaitu menyampaikan apa yang memang sepatutnya disampaikan, bukan menyembunyikannya (Tuhfatul Murid, 201-204).
Kepemimpinan Kharismatik, Bukan Gimik
Keempat karakter tersebut ialah cermin ideal untuk melakukan evaluasi pada pemimpin. Apabila masing-masing sudah tertanam di dalam diri seorang pemimpin, maka kharisma akan tumbuh sebagai kekuatan otentik dalam dirinya. Kenapa disebut otentik? Sebab kharisma itu muncul bukan disebabkan oleh polesan dari luar diri seseorang, tapi muncul dari dalam. Maka sifat dapat dipercaya (amanah), jujur (shidq), cerdas (fathanah) dan pandai menyempaikan hal yang semestinya disampaikan adalah value diri yang bersifat kualitatif. Kenapa hal demikian penting? Sebab di era teknologi sekarang kita sering kali tertipu oleh polesan citra luar seorang pemimpin yang belum tentu menggambarkan kualitas diri. Seseorang akan dengan mudahnya menampakkan dirinya melalui gimik politik. Hal demikian dipergunakannya sekadar menggaet suara, perhatian dan emosi masyarakat. Hal ini berbeda dengan kharisma yang hanya diperoleh dengan menumbuhkan nilai-nilai positif kepemimpinan dalam diri.
Soal ‘kharisma’, Max Weber, sosiolog berkebangsaan Jerman menerangkan hal tersebut dalam perspektif dia tentang seorang pemimpin. Menurutnya, kharisma bukanlah konsep atau gambaran yang bisa diperoleh sembarang orang, tapi oleh figur yang tergerak secara alamiah memimpin di masa-masa yang genting. Menurutnya, kharisma hadir sebagai karunia khusus jiwa dan raga; dan karunia itu diyakini sebagai hal supranatural. Weber melanjutkan bahwa kharisma bukanlah hal yang dituntun oleh sesuatu seperti uang, misalnya, yang berada dalam wilayah ekonomi rasional. Ia terlepas dari ruang-ruang semacam itu. Menurut Weber, hal ini dikarenakan mereka memahami posisi mereka sebagai pemimpin yang dituntun oleh kehendak ilahiah, siap bertanggung jawab di hadapan tuhan dan rakyat yang mereka pimpin. Para nabi, menurutnya, adalah pemimpin yang memiliki kharisma (Sosiologi, 295-298). Maka seharusnya bagi siapa saja yang menghendaki dalam dirinya jiwa kepemimpinan untuk menjadi pemimpin yang hakiki, hendaklah ia menumbuhkan kharisma, bukan hanya gimik belaka. Pun siapapun yang menghendaki pada arah kebaikan bersama, hendaklah ia berpihak pada seseorang yang tertanam dalam dirinya jiwa kepemimpinan yang kharismatik.
Wallahu a‘lam.