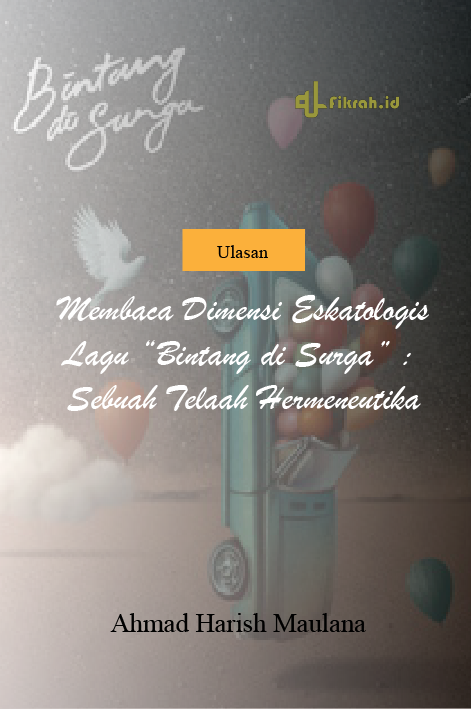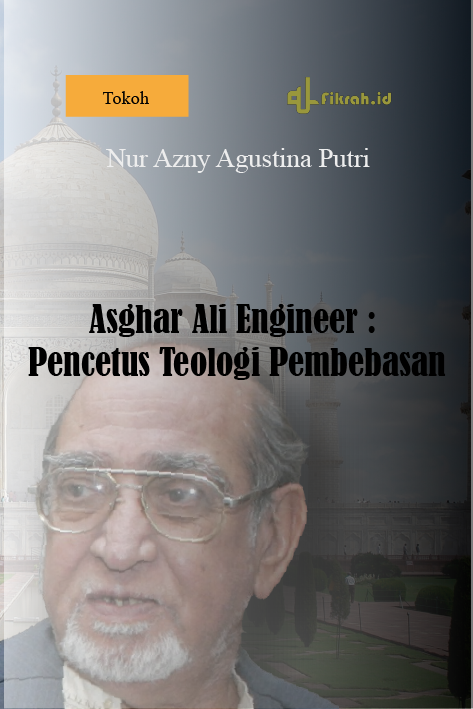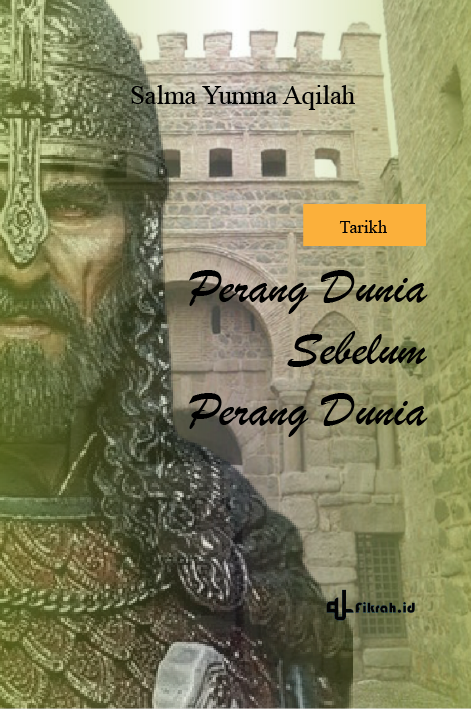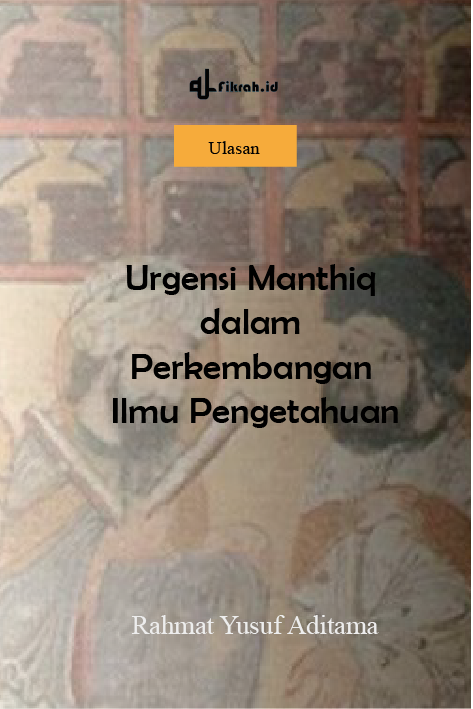Di kalangan pendengar musik tanah air, Peterpan adalah nama yang merujuk pada entitas grup band tersohor. Grup band yang sekarang berganti nama Noah itu telah mendulang banyak prestasi dan popularitas besar di Indonesia sejak awal eksisnya di era tahun 2000-an. Di antara prestasi bersejarah yang pernah diukir grup band asal Bandung itu adalah ketika album kedua mereka, yakni album “Bintang di Surga”, yang rilis pada tahun 2004 menjadi album dengan penjualan terlaris di Indonesia dalam kategori group band, dengan angka penjualan mencapai sekitar 3,2 juta keping, yang sontak, membuat nama Peterpan kian melambung tinggi.
Salah satu lagu fenomenal yang ada dalam album “Bintang di Surga” adalah lagu Bintang di Surga, yang juga dijadikan nama album. Tidak seperti band-band lain pada masanya yang kebanyakan selalu meluangkan masa berkaryanya dengan membuat setidaknya satu album khusus yang memuat lagu-lagu bertemakan religi, Peterpan termasuk yang tidak mengikuti tradisi itu. Peterpan tercatat tidak memiliki satu pun album religi. Pada suatu kesempatan wawancara, vokalis mereka, Ariel, pernah ditanya mengenai kenapa Peterpan tidak membuat album religi. Ariel menjawab, benar bahwa jika dilihat secara eksplisit, tak ada single maupun album Peterpan yang bertema religi, namun, tegas Ariel, jika pendengar mau memahami lebih dalam, beberapa lagu Peterpan ada yang secara inplisit menyiratkan makna religiusitas, yang salah satunya adalah lagu Bintang di Surga.
Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud menawarkan sudut pandang kepada pembaca untuk melihat dimensi ilahi dalam lagu Bintang di Surga sebagaimana yang diungkapkan Ariel tadi. Penulis melihat ada dimensi eskatologis yang tak mudah ditangkap hanya dalam sekali dengar di balik beberapa bagian lirik lagu Bintang di Surga. Untuk melihat dimensi eskatologis tersebut, penulis menggunakan bantuan teori hermeneutika.
Hermeneutika Dekonstruksi
Hermeneutika sendiri merupakan salah satu cabang dalam disiplin ilmu penafsiran atau interpretasi teks. Secara sederhana, hermeneutika dapat dipahami sebagai langkah lebih lanjut dari terjemah. Jika terjemah adalah kerja sekedar memindah bahasa suatu teks ke bahasa yang lain, maka hermeneutika lebih lanjut dan mendalam dari itu, yakni mengungkap makna yang “tersembunyi” di balik suatu teks (Hardiman, 2015). Di dalam teori hermeneutika, sebenarnya ada banyak sub teori berikut para penggagasnya. Salah satu sub teori itu, dan yang akan digunakan sebagai “pintu” untuk memasuki dimensi eskatologis dalam lagu Bintang di Surga kali ini adalah teori hermeneutika dekonstruksi. Salah satu tokoh terkenal penggagas teori ini adalah Jacques Derrida.
Dalam pembacaan melalui teori dekonstruksi ini, kita akan memosisikan lagu Bintang di Surga sebagai teks yang menjadi objek interpretasi. Derrida, sebagai pemilik dekonstruksi, menegaskan bahwa setiap teks seharusnya memiliki “hak kemerdekaan”-nya. Merdeka yang berarti bebas, yakni teks yang terbebas dan memiliki wajah independensinya tersendiri dari koridor konsepsi makna yang dimaksudkan oleh penutur teks itu sendiri (Derrida, 1998).
Dengan demikian, maka pembaca teks berhak untuk memahami dan menafsirkan ulang apa dan bagaimana substansionalitas sebuah teks, yang kemudian hasilnya bisa disesuaikan dengan relativitas kebutuhan konteks ruang dan waktu kehidupan pembaca teks. Demikian halnya yang akan kita lakukan terhadap lagu Bintang di Surga. Bahwa, terlepas dari apa yang dimaksudkan Peterpan sesungguhnya atas lagunya itu, kita sebagai pembaca dan pendengar, melalui kacamata dekonstruksi, berhak melihat Bintang di Surga dalam nuansa yang lain.
Bintang di Surga: Taswir Perjumpaan Manusia Dengan Tuhan
Barangkali akan berbeda dengan banyak pandangan orang pada umumnya terhadap lagu Bintang di Surga ini, bahwa penulis melihat ada dimensi eskatologis yang bisa kita resapi dalam beberapa bagian liriknya. Dalam lagu Bintang di Surga, penulis membaca ada sebuah rangkuman perenungan tentang potret kehidupan manusia dari awal diciptakan, diletakkan di muka bumi ini, menjalani titah dan amanat kehidupan dari Yang Maha Kuasa sampai batas ajal yang ditentukan, hingga puncaknya tatkala kelak akan berjumpa dengan bintang yang ada di surga, yang akan sama-sama kita ketahui apa atau siapa sesungguhnya sosok bintang itu. Kita mulai dari lirik berikut.
Masih ku merasa angkuh
Terbangkan anganku jauh
Langit kan menangkapku
Walau ku terjatuh
Empat larik lirik di atas memuisikan bagaimana jati diri, ambisi, hingga batas kesadaran manusia dalam mengarungi kehidupannya. Lirik “masih ku merasa angkuh”dapat dipahami bahwa pada sisi-sisi tertentu, manusia terlahir (juga) dengan keangkuhannya, tumbuh, dan bertindak dengan tak bisa memungkiri kecenderungan egoismenya. Egoisme tersebut biasanya hadir dalam bentuk keinginan maupun ambisi untuk dapat menjadi yang berkuasa, dominan, dan tak jarang hegemonik di antara entitas yang lain. Maka maklum jika kemudian “terbangkan anganku jauh”,di mana dalam background mentalitas seperti itu, manusia lantas menerbangkan angan-angannya sejauh mungkin, memasang berbagai target, cita-cita, maupun ekspektasi tinggi dalam hidupnya.
Walau kemudian kita diingatkan oleh lirik “langit kan menangkapku”, bahwa tak peduli sejauh apapun pengembaraan dan perjuangan manusia menggapai apa yang diimpikannya, sekeras apapun ia berusaha, harus tetap memiliki kesadaran bahwa manusia dan segala yang dimilikinya masih berada di bawah “langit”yang sewaktu-waktu bisa menangkapnya: masih berada di dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa, yang sewaktu-waktu dapat berkehendak untuk merubah-gagalkan rencana manusia hingga mematikannya kapanpun Dia mau. Dalam perspektif majaz isti’arah, diksi “langit” kerap dipakai untuk menggambarkan esensialitas ketuhanan maupun hal-hal besar dan tinggi lain yang memiliki pengaruh serta dominasi kontrolik atas hal-hal kecil di bawahnya (Al-Hasyimi, 1999).
Dan bila semua tercipta
Tanpa harus ku merasakan
Cinta yang tersisa, hampa hidup terasa
Tiga bait lirik di atas kiranya cukup menggambarkan perihal esensialitas hidup, tentang arti dan kebermaknaan hidup yang sesungguhnya. “Dan bila semua tercipta”, seandainya segala hal yang tercipta, yang ada di dunia ini menjadi milik kita seorang, akan tetapi jika itu “tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa”, tanpa kita tahu bagaimana cara “mencintai” segala yang kita miliki, mencintai dalam arti bijaksana dan penuh pertimbangan akan keseimbangan relativitas hak dan kewajiban antara kita dengan yang kita miliki, maka “hampa hidup terasa”, sudah barangkali tentu hidup akan terasa hampa, tak bermakna, dan sia-sia belaka. Hal tersebut selaras dengan salah satu ungkapan Jalaluddin Rumi, “Dengan hidup yang hanya sepanjang tarikan nafas ini, jangan tanam apapun kecuali cinta…”.
Bagai bintang di surga
Dan seluruh warna
Dan kasih yang setia
Dan cahaya nyata
Dan terakhir, empat bait lirik di atas bisa dibilang sebagai titik puncak dan klimaks dalam lagu ini. Bagian ini juga bisa disebut bagian paling bernuansa eskatologik. Tatkala mendengar lirik di atas, kita lantas membayangkan tentang sebuah entitas yang begitu tinggi, begitu agung, sekaligus begitu indahnya. Dari sudut renung hermeneutis-dekonstruktif, penulis memaknai bahwa bintang di surga yang disebut dalam lagu tersebut adalah Tuhan, Allah, yang akan bersama-sama kita lihat dan pandangi ketika di surga nanti.
Bahwa di surga nanti, kita tidak lagi hanya sekedar mengingat dan menghafal segala hal tentang Allah seperti ketika masih di dunia, akan tetapi kita akan sama-sama menyaksikan, merasakan kenikmatan yang paling puncak dari segala kenikmatan apapun, nikmat tiada tara: tenggelam dalam kenikmatan melihat Allah dengan seluruh warna-Nya: dengan seluruh pancaran asma’ul husna beserta sifat-sifat agung-Nya, dengan kasih yang setia-Nya, serta dengan Cahaya-Nya yang nyata. Dalam tradisi sufisme, momen ini biasa disebut nadhrah wajhillah (memandang Dzat Allah).
Referensi:
Al-Hasyimi, As-Sayyid Ahmad. Jawahir al-Balaghah. (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 1999).
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Terj. Gayatri Chakravorty Spivak; edisi koreksi. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998).
Hardiman, F. Budi. Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. (Sleman: Penerbit PT. Kanisius, 2015).