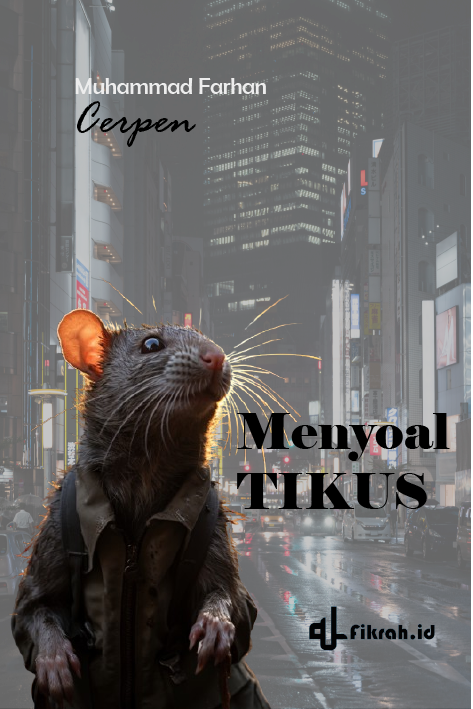Tiga tahun silam, kala mataku dimanjakan kemuning padi akhir tahun, juga Pak Urip yang masih sering menyapaku saat melintas dengan motornya. Aku masih sering berurusan dengan hama. Tikus-tikus di sini selalu membuatku jengkel. Pasalnya, aku pernah gagal panen. Hampir separuh dari perhitunganku meleset. Perencanaan delapan kuintal yang kuharapkan raib begitu saja. Bahkan, tidak hanya aku yang ditimpa kemalangan, orang-orang di sini pun serupa demikian. Tikus-tikus itu merangas, merusak bubu-bubu kawat kami. Serangan mereka sulit ditebak. Pengairan yang kurang maksimal ditambah hujan yang tidak menentu setiap harinya membuat kami harus ekstra berjaga. Tidak sedikit dari kami yang berkemul tebal menahan tusukan angin malam di dangau sembari menggerakkan orang-orang sawah yang kami pasang. Namun naas, semua tetap sia-sia, tikus-tikus itu melebihi kecerdasan kami.
Dari pengalaman yang pahit itu aku mulai memahami sifat tikus. Cerdik dan rakus. Ya, hanya dua itu yang kusimpulkan dari sekian banyak sifat yang ia miliki. Tidak salah sebetulnya ia memakan padi-padi di sawah, toh secara naluriah ia adalah omnivora liar di alam. Namun yang kutanyakan adalah mengapa harus padi milikku?, atau bahkan padi kami semua?!. Sawah kami dikelilingi banyak semak belukar, pepohonan berry, pepohonan kapuk, pepohonan pisang yang tak bertuan, hingga bambu-bambu tinggi. Kiranya itu sangat cukup untuk kebutuhan pangan populasi mereka. Namun nyatanya mereka memilih merampas satu-satunya sumber penghasilan hidup kami.
Soal Pak Urip, sebelum hari itu terjadi, semasa Pak Urip menjabat menjadi kepala desa di sini, aku tak pernah sedikitpun tahu keburukannya. Sejak pemilihan kepala desa, kami semua yakin jika ia tak seperti kades sebelumnya yang gampang manjalin tandem kerja dengan pembesar-pembesar pabrik. Keberadaan sawah kami terancam oleh pabrik-pabrik itu. Bisa dibilang tanda tangan orang penting itu mahal. Untung saja ia sudah mengakhiri masa jabatannya dan tidak terpilih untuk kedua kalinya.
Tidak hanya persoalan lahan sawah yang rawan digilas pabrik, ancaman gagal panen pun menyelimuti kami. Bahkan janji-janji pupuk subsidi pupus begitu saja ketika penangkapan waktu itu terjadi. Mungkin dalam jangka panjang, sampai habis masa jabatan Pak Urip, kami tidak dihadapkan lagi pada proses pendirian pabrik-pabrik. Tapi masalah besar bukan berarti hilang begitu saja bersama Pak Urip yang juga pergi meninggalkan kami. Justru tikuslah ancaman terberat yang harus kami hadapi.
Oh ya, perkenalkan, aku ini petani yang lulusan SMU. Tidak banyak orang memilih bekerja sepertiku. Ancaman tergusurnya lahan persawahan atas parbrik-pabrik di sana membuatku memilih meneruskan pekerjaan bapakku. Mungkin bekerja di balik deru mesin-mesin pabrik lebih menjamin nominal gajinya, tapi rezeki tidak soal uang bukan?.
Bangku sekolah mengajariku banyak hal. Aku teringat pada tikus. Sedikit banyak aku tahu hewan cerdik ini. Akan kuberitahu pada kalian banyak hal soal tikus. Pertama, ia adalah hewan yang cerdik dan berpaham pola. Jangan harap tikus mudah dibodohi hanya dengan sekali percobaan dan dengan model perangkap yang sama. Kedua, mereka itu komunal. Tapi aku curiga, komunal yang mereka bangun adalah sekelompok pemburu yang saling bekerja sama. Mereka saling berunding untuk menerobos parit-parit kami, merusak jaring bubu-bubu kami, hingga taktik jitu mencari jalur tanah yang kering. Ketiga, walau terbilang hewan yang kecil, sesungguhnya ia adalah pemanjat, perenang, penggigit yang ulung. Setidaknya ada enam puluhan lebih spesies tikus di dunia ini. Gigi-gigi mereka kuat dan mampu mengoyak apa saja yang ditemuinya. Coba bayangkan betapa menakutkannya hewan ini jika kalian tak waspada. Sepertinya mereka juga sulit untuk kenyang. Betapa rakusnya mereka dalam menyantap semua benda di dunia ini. Bahkan andai gigi mereka diciptakan seperti gergaji mesin, mungkin kayu-kayu dangau kami hingga berbagai macam pepohonan di seberang sudah raib.
Tak berselang lama, tiga mobil polisi melintas di jalan dusun. Aku masih duduk termangu di atas dangau sembari menggerakkan tali orang-orangan sawah. Mungkin beberapa orang di sekitarku juga tertegun. Pasalnya kami melihat pemandangan itu terakhir kalinya sejak rumah Pak Urip digerebek aparat.
Perlu kalian ketahui, dusun kami beruntung sebetulnya. Hal itu atas sebab kepala desa kami adalah orang dari sini. Ya, Pak Urip adalah orang paling tajir sedesa. Bisa dipastikan andaikata ia mencalonkan diri dua kali pun akan tetap menang. Namun sayang, keberuntungan itu tak kami dapatkan. Bukannya bangga, justru kami benar-benar malu manakala Pak Urip menggelapkan dana desa sejumlah puluhan juta.
“Aku curiga masalah Si Urip belum selesai.” Pak Din tiba-tiba datang mendekat padaku. Sembari mengelap peluh ia meneguk air dalam ceret.
“Memang gimana ceritanya sih Pak?,” selidikku.
“Ceritanya rumit,” ia kembali meneguk air di ceret. “Oke, begini,” ia lalu duduk di sebelahku sambil menghidupkan sebatang kretek.
“Setahuku dia korupsi uang pembenahan jalan kabupaten. Jalan utama yang berjejer pabrik-pabrik itu punya anggaran besar. Selain bersumber dari pendapatan belanja dari pusat, juga ada setoran dari pabrik-pabrik itu. Urip ini belum seberapa. Dia hanya puluhan juta. Kalau kau tahu, kades sebelum Si Urip dapat seratus dua puluh juta.”
Ia terus bercerita panjang lebar sampai-sampai ia berucap dengan nada lirih, “Semua tergantung pengamanannya. Si Urip lagi apes aja. Coba ia punya orang-orang yang membackup pasti tidak demikian.”
Kini kutahu ternyata Pak Din juga orang-orangnya kades sebelumnya. Ia tahu betul segala carut-marut proyek pembangunan infrastruktur yang tak dapat penanganan khusus desa ini. Kini, setelah kades sebelumnya lengser, dia kembali ke sawah menggarap lahannya sendiri, menjadi petani seutuhnya. Sungguh bengis memang mereka-mereka yang tak pernah kenyang itu. Aku tak mampu membayangkan betapa banyaknya uang yang berlabel ratusan juta, sedang aku panen tertinggi tidak pernah menembus angka itu.
========
Pagi ini aku membiarkan beberapa tikus melintas di depan radar mataku. Sepertinya mereka juga bingung akan wajahku yang tak berselera. Mereka berlari-lari kecil melintasi pinggiran parit sambil sesekali menoleh ke arahku. Namun aku tak terpancing. Kubiarkan mereka sesuka hati memilih padi-padi milikku. Toh mereka tidak akan merugikan rezekiku hari ini. Dan kini kusadari, jika tikus-tikus semungil mereka tetap masih waras. Ada banyak tikus di luaran sana yang jauh tidak waras. Mereka justru memakan dana desa hingga uang proyek jalan raya untuk kemaslahatan warga,
Entah apa yang terjadi kemarin, pagi ini aku benar-benar tertegun. Hening pagi membawa kabar bahwa hari-hari dalam hidup adalah serangkaian tragedi yang saling berkesinambungan. Antara percaya dan tidak, pagi ini batang hidung Pak Din sudah tidak nampak. Kemungkinan besar ia sudah menghadap meja penyidik. Usut punya usut, seratus dua puluh juta yang ia ceritakan kemarin ternyata juga masuk dalam kantongnya. Ia mungkin tak sadar jika kemarin mobil polisi yang datang mengirim sinyal padanya. Entah Pak Din atau Pak Urip, tikus sawah, juga tikus-tikus di depan meja penyidikan, semua masalah-masalah kerakusan ternyata benar-benar serangkaian tragedi yang berkecamuk di pikiranku.