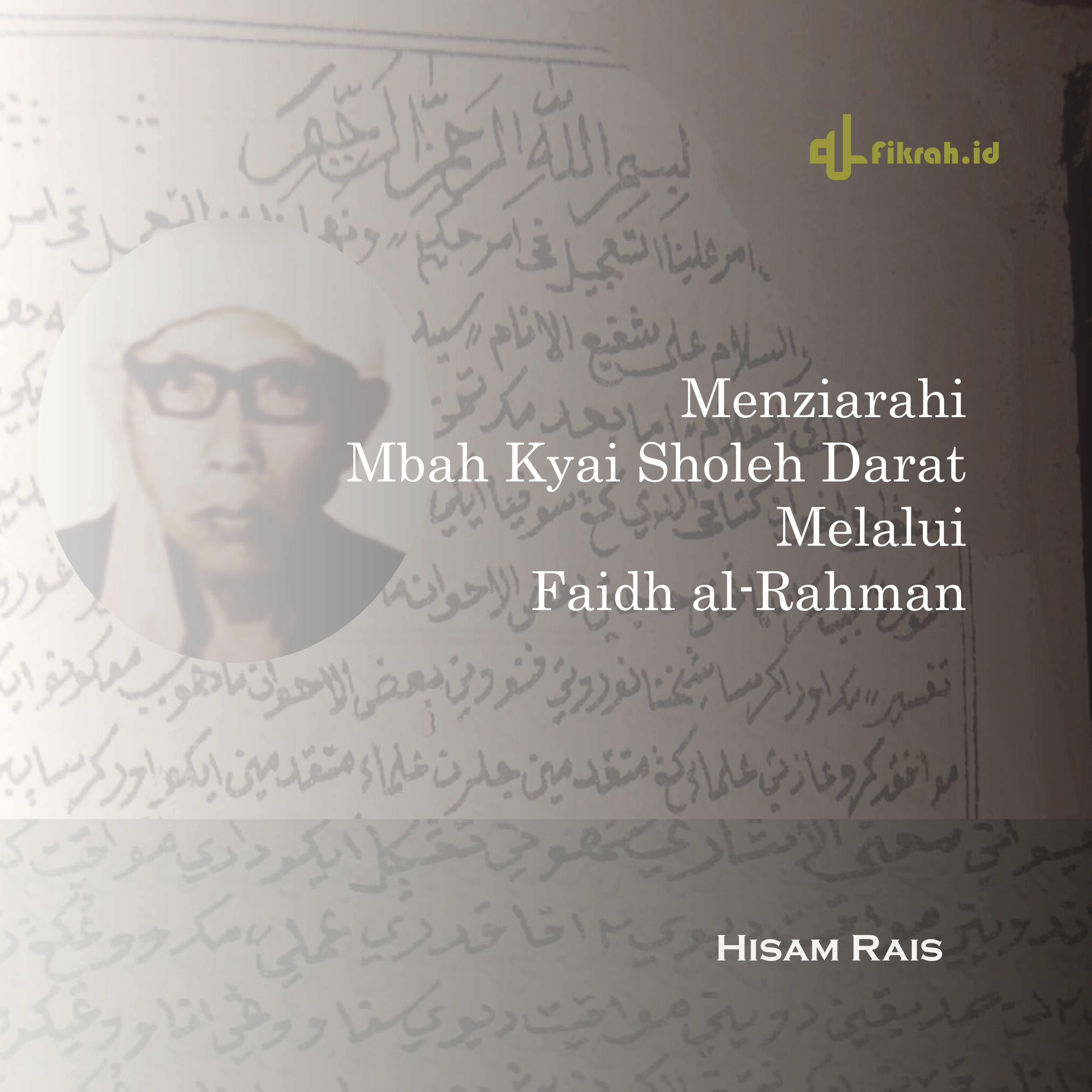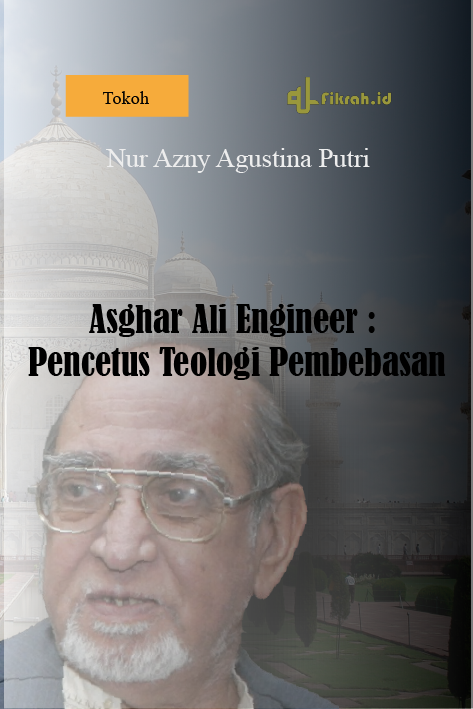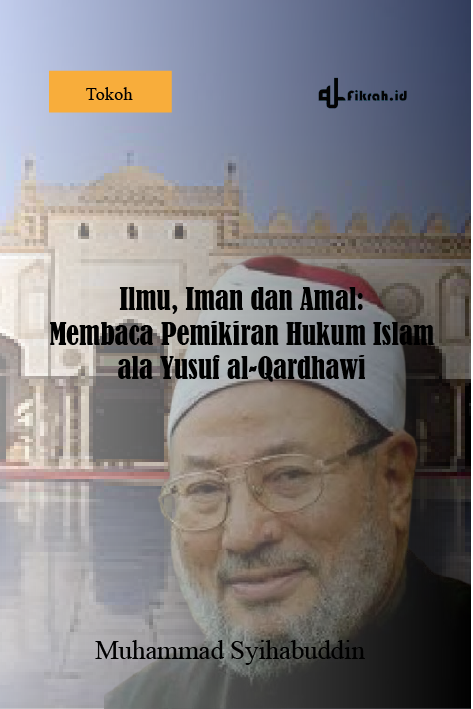Menulis tema ini adalah satu spirit tersendiri bagi saya, yang kiranya terlalu naif jika harus mengatakan sekedar mengisi kolom rubrik saja. Tafsir Faidh al-Rahman telah mengisi hari-hari saya di Jogja kala itu, di ambang perjuangan spirituil di pesantren dan juga perjuangan formil menyelesaikan tugas akhir skripsi. Ya, dengan lugas saya harus mengatakan bahwa tafsir legendaris ini menjadi mahakarya ulama nusantara yang harus mendapat tempat tertinggi bagi semua karya-karya tafsir Nusantara lainnya.
Sembari tiada henti mentawassuli Mbah Kyai Sholeh, saya berusaha menyelami hasil scan manuskrip yang beberapa bagiannya robek dan termakan rayap itu. Hanya ketakjuban yang mendahului dari semua rasa penasaran saya. Mungkin skripsi yang saya selesaikan juga bukan sebab kepiawaian saya mendalami manuskrip, namun berkat ridho dan keberkahan Mbah Kyai Sholeh yang telah mengizinkan alfaqir ini sejenak bisa duduk bersimpuh mempelajari mahakaryanya.
Saya tak begitu etis kiranya membedah secara dalam karya yang jelas-jelas adalah buah karya dari seorang ulama, sufi besar, alim allamah, guru nusantara, hingga sosok dengan ketinggian derajat dan kemuliaan sekelas beliau. Saya hanyalah santri yang entah bagaimanapun juga tidak akan bisa menggarami lautan kelimuan guru-guru saya. Dalam kesempatan itu saya kiranya sedang meneropong jauh, melihat, menganalisis, mentafakkur, dan sekaligus melucuti diri dengan keterbatasan kacamata saya tentang bagaimana Tafsir Faidh al-Rahman telah mencatat sejarah besar, baik bagaimana ia dilahirkan, misi yang dibawa, hingga dampak-dampak yang spektakuler dirasa.
Dengan segala keterbatasan, saya mencoba melihat karya besar itu dari latar belakang sosiologis-antropologis dan menghasilkan satu pembacaan bahwa Tafsir Faidh al-Rahman tidak sekedar karya ilmiah yang bermuatan spirit relijius, namun juga menyentuh wilayah-wilayah lain yang tidak saya bayangkan pada awalnya. Lebih jauh Tafsir Faidh al-Rahman bagi saya adalah bentuk perlawanan, penolakan hegemonis, hingga spirit perwujudan jati diri bangsa.
Kyai Sholeh Darat dan Pendudukan Belanda
Pada abad 19 adalah masa yang tercetak tebal dengan masa kolonialisasi Belanda. Keberadaan Belanda bagi masyarakat pribumi merupakan sebuah ancaman di segala bidang. Nyatanya mereka datang bukan hanya untuk tujuan penguasaan wilayah, melainkan juga merampas kekuasaan politik, ekonomi, budaya dan agama.
Dalam anggapan kaum muslim Nusantara, labelisasi kolonialisme adalah hegemoni penjajah. Bagi para Kyai di Nusantara, mereka tetaplah orang kafir yang semena-mena merampas kebebasan hidup dan beragama di Nusantara. Seruan-seruan jihad kian bermunculan dan diletuskan dalam dua spirit ; keimanan dan kebangsaan. Selain rupa peperangan, banyak usaha lain dilahirkan seperti; pendidikan yang mencakup pendidikan baik agama maupun formal dan perlawanan dalam bentuk penguatan budaya.
Dalam bidang pendidikan (agama dan formal) khususnya, telah banyak tokoh Kyai dan ulama mengusahakan peneguhan pijakan kaki aspek lokal supaya tidak tergerus oleh budaya dan pemikiran-pemikiran yang merugikan masyarakat pribumi. KH Sholeh Darat adalah salah satu pionir dari banyak tokoh nasional yang berjuang di bidang pendidikan keagamaan. Beliau mendirikan pesantren yang ditujukan kepada masyarakat tingkat lanjut atau telah memiliki bekal agama sebelumnya.
KH Sholeh Darat memiliki nama lengkap Sholeh Ibnu Umar, lahir di Desa Kedung Jemblung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada kisaran tahun 1820 M. Mbah Kyai Sholeh—sapaan akrab di kalangan santri, merupakan putra dari seorang ulama bernama KH. Umar yang merupakan pejuang anti kolonial Belanda dan salah satu yang ikut serta dalam perang pada masa Pangeran Diponegoro. Dari nasab ini bisa dikatakan telah mengalir darah perjuangan membela tanah air dan ditambah Mbah Kyai Sholeh mendapat banyak pendidikan dari ayahnya sehingga tertanam kuat dalam benaknya jiwa-jiwa nasionalisme.
Perjuangan Mbah Kyai Sholeh dalam melawan penjajah terwujud dengan spiritnya dalam mendirikan pesantren dan menulis banyak karya berbentuk kitab, yang bertujuan untuk menghilangkan buta ilmu. Pasalnya, kondisi yang ironi tengah mengendap dalam kehidupan masyarakat pribumi saat itu yaitu buta huruf dan buta moral. Bagi Mbah Kyai, hal itu merupakan jalan yang efektif ditempuh pada masa itu karena perlawanan melalui agresi belum juga mendapatkan titik terang, terlebih setelah kekalahan masyarakat melawan Belanda saat Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dari peristiwa kemunculan spirit pendidikan yang sporadis itu, Kolonial Belanda memandang ulama sebagai tokoh yang perlu diawasi karena pengaruh terhadap masyarakat cukuplah besar. Hal demikian membuat ulama berpikir ulang untuk melancarkan agresi militer sehingga penguatan terhadap masyarakat melalui ajaran agama merupakan hal yang paling efektif untuk dilakukan demi membendung distorsi dari pengaruh Belanda.